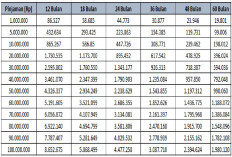Idul Fitri yang Suci dan Manusiawi

--
* Dr. Wardah Nuroniyah
(Dosen UIN Syahidda, Jakarta)
TRADISI yang menyertai puasa bulan puasa Ramdhan sampai menyambut Idul Fitri di Indonesia sangat tipikal “negeri Pancasila”. Di Indonesia bulan Ramadhan dan Idul Fitri, sudah seperti menjadi milik bangsa dan semua agama di Indonesia.
Perhatikan saja, menjelang bulan Ramadhan, orang-orang Indonesia banyak yang pergi ke komplek pemakaman. Tujuannya untuk nyekar (tabur bunga di atas makam orang tua dan keluarga yang telah “pergi” mendahuluinya) serta berdoa untuk kebaikan mereka di alam sana.
Menariknya, tradisi nyekar dan berdoa untuk “mereka” di alam kubur tersebut, tidak hanya dilakukan umat Islam. Tapi juga umat bergama lain di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Bahkan agama-agama lokal seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan lainnya melakukan hal yang serupa. Seakan sudah ada kesepakatan dan sepemahaman bahwa hari-hari suci umat Islam tersebut adalah haru-hari suci bagi mereka juga.
Fenomena ini menggembirakan. Karena ritual-ritual agama di Indonesia yang beraneka nama itu seakan “menyatu” dalam nuansa “spiritualitas” yang sama. Hal ini terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi, penuhnya gerbong kereta api, dan banyaknya orang mudik jelang bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri.
Mereka, masyarakat dari berbagai agama – seperti halnya umat Islam – ingin pulang kampung dan melakukan ritual mudik untuk “bertemu” dengan orang tua dan keluarganya yang sudah mendahuli pergi ke alam baka.
Apa yang bisa kita katakan tentang fenomena mudik massal dari semua etnis dan agama di hari-hari suci umat Islam tersebut? Proses kulturalisasi dari pluralisme sedang berjalan di Indonesia. Proses kulturalisasi pluralisme tersebut berjalan secara alami, tanpa bisa dibendung dengan “ajaran dan paham” apa pun.
Penulis Denny JA, Phd founder Lingkaran Survei Indonesia, menyatakan bahwa saat ini, sedang terjadi penyatuan tradisi-tradisi agama melalui proses kulturalisasi. Pada saatnya, tulis Denny JA, akan muncul penyatuan “irisan-irisan” berbagai pandangan agama. Dan ini akan memperkuat sendi-sendi pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Fenomena ini, tidak hanya terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Tapi juga di Amerika yang myoritas Kristen; di Cina yang mayoritas Kong Hu Cu; dan Jepang yang mayoritas Shino.
Di Hari Natal, misalnya, semua rakyat Amerika – dari agama apa pun -- larut dalam perayaan kelahiran Yesus tersebut. Di Cina, semua rang – apa pun agamanya, bahkan yang atheis sekali pun – larut dalam ritual mudik Gong Xi Fa Cai.
Hal yang sama terjadi di Jepang. Festival malam Chichibu dalam perayaan hari bersyukur kepada “Kami-Kami” yang menyejahterakan rakyat Jepang, kini tak hanya dirayakan orang yang beragama Shinto. Tapi juga dirayakan mereka yang beragama Hindu, Budha, dan Islam di Jepang.
Keberagamaan di Jepang, sangat menarik. Mayoritas penduduk Jepang menganut agama lebih dari satu. Bagi orang Jepang, semakin punya banyak Tuhan (menganut lebih dari satu agama) semakin baik. Karena orang bersangkutan mempunyai banyak Tuhan yang diminta pertolongannya.
Salahkah mereka dalam beragama? Wallahu a’lam. Jika kebaikan agama dilihat dari perilaku masyarakatnya, keberagamaan di Jepang bisa dikataakan berhasil. Berhasil dalam pengertian bahwa moralitas agama Shinto teraplikasi dengan baik di masyarakat. Jepang adalah negeri maju yang masyarakatnya sangat takut korupsi dan mengambil hak orang lain. Orang dengan jabatan setingkat menteri, misalnya, ketahuan korupsi ribuan dolar, langsung mengundurkan diri.
Sumber: