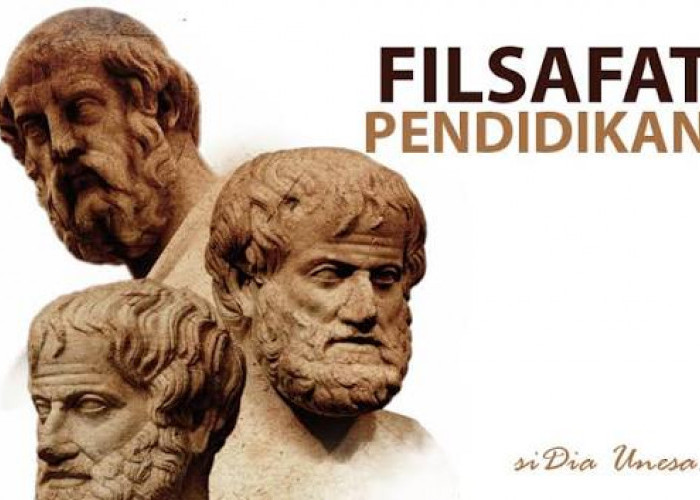Polemik Stasiun Cirebon: Antara Naming Rights dan Nilai Budaya

Dr. Sitti Maesurah S.IKom M.IKom, Dosen dan Peneliti aktif bidang Komunikasi Bisnis Antar Budaya. FOTO: IST/ RAKYAT CIREBON--
Batik Trusmi selama ini menjadi representasi kekuatan budaya ekonomi Cirebon di kancah nasional.
Namun, dalam konteks komunikasi lintas budaya, branding tidak sekadar soal promosi visual. Ia adalah proses negosiasi makna dan legitimasi sosial.
Teori Anxiety/Uncertainty Management oleh Gudykunst (1998) menjelaskan bahwa masyarakat akan merespons perubahan simbolik dengan kecemasan bila tidak dilibatkan dalam proses komunikasi.
Kecemasan sosial itu muncul karena hilangnya kendali terhadap makna bersama.
Reaksi publik Cirebon terhadap perubahan nama menandakan defisit komunikasi empatik, bukan sekadar penolakan ekonomi, tetapi ketidaknyamanan kultural terhadap cara keputusan diambil.
Dalam komunikasi bisnis antar budaya, keberhasilan kolaborasi bukan hanya diukur dari kesepakatan kontraktual, melainkan dari penerimaan sosial yang berakar pada rasa hormat terhadap nilai lokal.
Dimensi Regulasi dan Legitimasi Sosial
Perdebatan penamaan Stasiun Cirebon Kejaksan tidak hanya berkaitan dengan aspek simbolik, tetapi juga menyentuh wilayah hukum, tata kelola aset publik, dan legitimasi sosial dalam komunikasi bisnis.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa setiap elemen yang memiliki nilai sejarah termasuk nama, arsitektur, dan fungsi sosial merupakan bagian dari identitas budaya yang wajib dilindungi.
Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelestarian tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup pelestarian makna dan nilai yang melekat pada warisan budaya tersebut.
Dengan demikian, nama “Kejaksan” tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kawasan Cirebon sebagai simpul peradaban dan pintu gerbang budaya pesisir Jawa Barat.
Selain UU tersebut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian juga memuat prinsip bahwa setiap perubahan nomenklatur stasiun harus mempertimbangkan aspek sejarah dan persepsi publik, serta dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Artinya, kebijakan penamaan stasiun tidak boleh diperlakukan sebagai ranah bisnis semata, melainkan keputusan publik yang menyentuh identitas kolektif warga.
Dalam konteks komunikasi bisnis antar budaya, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar persoalan formalitas hukum, melainkan juga pesan moral yang menunjukkan sensitivitas budaya dan tanggung jawab sosial korporasi.
Hal ini sejalan dengan teori Corporate Legitimacy (Suchman, 1995) yang membagi legitimasi menjadi tiga bentuk:
Sumber: